Pengantar Kumpulan Cerpen Ba karya Riyono Pratikto
Oleh: Sawali Tuhusetya
Karya-karya Riyono Pratikto (RP), khususnya cerita pendek (cerpen) yang lahir pada sekitar tahun 1950-an, agaknya belum semua terpublikasikan. Situasi politik Orde Baru yang cenderung represif terhadap kreativitas sastrawan yang dinilai tidak sehaluan politik dengan penguasa setidaknya ikut berpengaruh terhadap publikasi karya-karya sastrawan, termasuk RP. Padahal, cerpen-cerpennya memancarkan pesona kemanusiaan yang tidak kehilangan daya pikat meskipun zaman terus berubah. Cerpen-cerpennya membumi. Hampir tak pernah ditemukan cerpen-cerpen karya sastrawan kelahiran Ambarawa, Jawa Tengah, 27 Agustus 1932 ini yang berbicara tentang narasi dan persoalan besar yang rumit dan kompleks.
![rev]() Dalam situasi semacam itu, upaya untuk mendokumentasikan dan memublikasikan karya-karya sastrawan yang meninggal 30 Oktober 2005 ini menjadi penting dan relevan untuk memperkaya khazanah sastra Indonesia mutakhir. Penting dan relevan bukan sekadar untuk menunjukkan bukti bahwa negeri ini memiliki sosok sastrawan yang rendah hati dan konsisten, meskipun tekanan politik rezim Orde Baru nyata-nyata telah menyingkirkannya dari panggung kesusastraan Indonesia mutakhir. Juga bukan sekadar latah untuk mengenang romantika kreativitas seorang RP pada masa suburnya dalam berkarya, melainkan lantaran dari sisi literer karya-karyanya memang sangat layak untuk diapresiasi para pencinta, pemerhati, dan pengamat sastra.
Dalam situasi semacam itu, upaya untuk mendokumentasikan dan memublikasikan karya-karya sastrawan yang meninggal 30 Oktober 2005 ini menjadi penting dan relevan untuk memperkaya khazanah sastra Indonesia mutakhir. Penting dan relevan bukan sekadar untuk menunjukkan bukti bahwa negeri ini memiliki sosok sastrawan yang rendah hati dan konsisten, meskipun tekanan politik rezim Orde Baru nyata-nyata telah menyingkirkannya dari panggung kesusastraan Indonesia mutakhir. Juga bukan sekadar latah untuk mengenang romantika kreativitas seorang RP pada masa suburnya dalam berkarya, melainkan lantaran dari sisi literer karya-karyanya memang sangat layak untuk diapresiasi para pencinta, pemerhati, dan pengamat sastra.
Ditilik dari kisah-kisah yang diangkat ke dalam cerpen-cerpennya, RP bisa digolongkan sebagai sosok sastrawan yang sangat dekat dengan rakyat kecil dalam arti yang sesungguhnya. Nasib “wong cilik” tidak semata-mata dijadikan sebagai objek, tetapi dijadikan sebagai subjek penggarapan cerita yang disentuh dengan naluri kemanusiawian yang mengharukan. Cerpen-cerpennya mengalir hawa kemanusiaan yang cukup kuat. Setiap peristiwa keseharian yang dijadikan tema cerpen-cerpennya direnungkan secara sublimatif, dibedah, dan diolah dengan menggunakan bahasa sederhana, tetapi indah. Ada pesan-pesan moral kemanusiaan yang senantiasa terpancar dalam setiap cerita, tetapi jauh dari kesan menggurui.
Yang menarik, hampir setiap cerpen senantiasa mengandung suspense; serba tak terduga, dan seringkali membuat kening pembaca berkerutan. Ada bumbu mistis, angker, dan menyeramkan. Bisa jadi, bumbu-bumbu semacam itu merupakan gambaran terhadap realitas tradisi hidup masyarakat tahun 1950-an –ketika cerpen-cerpen tersebut dibuat– yang masih kental dengan nuansa takhayul dan klenik. Membaca cerpen-cerpen RP mengingatkan kata akan gambaran realitas masyarakat pasca-revolusi fisik yang serba “anomie”. Secara lahiriah, masyarakat sudah mulai terbebas dari kungkungan penjajah, tetapi secara batiniah masih terikat pada nilai-nilai tradisional yang masih sangat kuat mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi masyarakat “anomie” semacam itu setidaknya menjadi ilham tersendiri bagi RP untuk memberikan semacam “kesaksian literer” melalui teks-teks cerpen yang lahir dari tangannya. Sebagai sastrawan yang selalu bergelut dengan dunia imajiner, realitas-realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agaknya menjadi “kegelisahan” tersendiri bagi RP untuk berproses kreatif.
***
Sebagai sastrawan yang memilih genre cerpen sebagai media kreatifnya, tentu saja sah-sah saja RP menggarap cerpen-cerpennya dengan nuansa kisah semacam itu. Setiap pengarang memiliki kepekaan dalam menangkap setiap geliat peristiwa di sekitarnya. Setiap peristiwa tentu saja tidak hanya akan berhenti sebagai sebuah peristiwa sebagaimana layaknya sebuah berita yang ditulis seorang jurnalis. Justru di sinilah kepekaan dan kreativitas seorang pengarang diuji. Kepekaan intuitif dan “keliaran” imajinasi menjadi sebuah pergulatan kreativitas tanpa henti, sehingga sebuah peristiwa keseharian tak sekadar berhenti sebagai sebuah peristiwa semata, melainkan menjadi adonan kisah yang mengundang daya pikat dan daya tarik tersendiri buat pembaca. Dengan kata lain, kemampuan menafsirkan sebuah peristiwa menjadi tuturan kisah yang mampu menyentuh nurani kemanusiawian pembaca benar-benar menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang pengarang.
Dari sisi ini, RP bisa dibilang sebagai pengarang yang sangat berhasil dalam menafsirkan setiap peristiwa menjadi dedahan kisah yang menyentuh nurani dan mengharukan. Setiap peristiwa dikuliti, diolah, dan disuguhkan kepada pembaca menjadi sebuah adonan kisah yang kaya rasa dan kaya warna. Satu hal yang tidak bisa dilupakan dalam setiap cerpennya adalah mengaitkan peristiwa keseharian yang terekam ke dalam ceruk imajinasinya dengan situasi mistis, seram, bahkan menakutkan. Saya pikir, hal ini lumrah terjadi dalam sebuah teks fiksi, khususnya cerpen.
Simak saja 20 cerpennya dalam antologi ini. Dalam cerpen “Pembalasan pada Manusia”, misalnya, ada balutan suasana yang cukup mencekam dan menyeramkan. Seseorang yang memercayai arloji berhiaskan gigi orang yang telah meninggal yang ditemukan saat menggali pekarangan dekat rumahnya sebagai “azimat” membuat gempar warga. Lelaki pemakai azimat itu mendadak berubah seperti harimau buas. Anak dan isterinya tewas mengenaskan dengan kepala dan dada yang robek-robek dengan darah berceceran di lantai kamar. Karena tak sanggup menghadapi amukan warga, lelaki yang telah berubah menjadi binatang buas itu tak berdaya. Tubuhnya babak-belur dihajar massa yang kalap. Ketika hampir mati, satu tusukan bambu runcing mengenai gigi di arloji sakunya hingga akhirnya meninggal. Anehnya, si “lelaki harimau” itu merasa bahwa yang dimakan bukan anak dan isterinya, melainkan semangka ranum yang telah membangkitkan air liurnya.
Demikian juga, dalam “Dalam Kereta Api”. Cerpen ini semula mengalir seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sebuah kereta api. Penumpang berdesak-desakan dan suara bising. Namun, perjalanan kereta mulai tampak aneh ketika setiap penumpang bebas turun di mana pun mereka mau. Yang lebih aneh, masinis sepertinya paham betul dengan kemauan penumpang tanpa harus ditanya. Plot cerpen memang terkesan meloncat-loncat. Bahkan, di dalam cerpen ini juga dikutipkan beberapa terjemahan yang dinukil dari ayat suci Alquran. Cerpen ini ditutup dengan dialog antara tokoh “aku” dan seorang penumpang. Suasana mistis cukup terasa selama mengikuti perjalanan kereta api ini, seperti berada di “dunia lain”. Yang mengejutkan, tokoh “aku” didoakan oleh seorang penumpang agar mendapatkan kematian yang sempurna? Wow…. Semacam “kereta hantu” yang pernah menghebohkan warga masyarakat sekitar rel kereta api beberapa waktu yang lalukah? Ya, ada unsur surealis yang cukup kuat dalam cerpen ini; antara dunia realitas dan dunia “sonyaruri” menyatu dalam sebuah tuturan kisah yang cair sekaligus nglangut.
Nada dan suasana mistis juga bisa ditemukan dalam “Jalangkung”. Dituturkan, sosok misterius yang selalu hadir dalam pertemuan sastra membuat seorang sekretaris perkumpulan penasaran. Sosoknya belum pernah dilihat, tetapi namanya selalu mengusiknya. Setiap pertemuan, si sekretaris berupaya untuk menemuinya, tetapi selalu gagal. Ada yang menyimpulkan bahwa sosok misterius itu sesungguhnya adalah roh yang sudah tidak lagi hidup di dunia. Akhirnya, ada yang mengusulkan agar dipanggil melalui jalangkung yang konon diyakini bisa menjadi perantara untuk memanggil roh orang yang sudah meninggal. Aneh, ternyata Jalangkung dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan menuliskannya di sebuah batu dengan kapur tulis. Pada sebuah pertemuan sastra, tiba-tiba saja muncul seseorang bertubuh kurus yang namanya pernah diundang Jalangkung. Si kurus ini dalam pertemuan tersebut membacakan sajak-sajaknya. Ketika ditanya, mengapa selama ini tidak pernah memperkenalkan diri dalam pertemuan sastra? Si kurus yang selama ini diyakini sebagai sosok misteris menjawab bahwa dia berasal dari keluarga miskin. Jika alamatnya ditulis, takut diminta uang iuran. Hemm …. Sebuah cerpen yang menyentil bagi penggiat sastra “tempo doeloe” yang sering menarik iuran untuk menggelar sebuah pertemuan. Suasana mistis yang dibangun dalam cerpen ini memang tidak terlalu kental. Agaknya, pengarang hanya sekadar ingin memberikan gambaran terhadap realitas budaya masyarakat saat itu yang sering menggunakan “Jalangkung” sebagai medium spiritual untuk “iseng” memanggil roh orang yang sudah meninggal.
Suasana yang sangat menyentuh dan mengharukan dapat disimak pada cerpen bertitel “Haus”. Cerpen ini bertutur tentang seorang gadis yang tiba-tiba menyembul dari genteng rumah seorang nenek. Tangannya menggapai ke angkasa, lantas mulutnya menganga meminum air yang tumpah dari langit. Menurut si nenek, anak perempuannya yang minum air hujan sebenarnya sudah meninggal akibat sakit. Menurut dukun yang mengobatinya, selama sakit tidak boleh diberi minum setetes pun, sebab bisa mengakibatkan kematian. Sampai akhir hayatnya, si nenek juga tidak memberikan air minum, meskipun anak gadisnya mengeluh kehausan. Ketika tokoh aku menengok kamar si gadis, kamar itu kosong dan hanya ada sebuah bale dengan tikar yang kelihatan tertutup debu. Ya, sebuah kisah yang menggambarkan betapa kuatnya kepercayaan masyarakat saat itu terhadap otoritas seorang dukun dalam menyembuhkan penyakit. Apa yang dikatakan sang dukun dianggap sebagai “sabda” tak terbantahkan, meskipun secara medis dan logika sangat tidak masuk akal. Secara tersirat, ada pesan moral sang pengarang yang cukup kuat dalam cerpen ini. Otoritas sang dukun dimentahkan oleh fakta “imajiner” bahwa pada akhirnya si gadis, anak sang nenek tetap tak bisa diselamatkan nyawanya meski sang nenek telah mengikuti pesan sang dukun yang melarang anak gadisnya minum setetes air sekalipun. Bahkan, almarhumah sering menengadahkan wajahnya ke langit melalui kamar “abadi”-nya untuk meminum air hujan.
Cerpen “Pada Sebuah Lukisan” menampilkan adonan kisah yang cukup tragis. Sebagai pelukis, tokoh aku merasa kagum dengan raut wajah lelaki yang dilukisnya. Berbadan besar dan wajahnya terlihat bengis, tetapi ada sifat lembut dan kelemahannya. Ketika menghadapi lelaki itu, tokoh “aku” merasa tak sadarkan diri dan seolah mengapung di alam lain. Si lelaki yang dikaguminya itu bercerita tentang suasana perang melawan Belanda dan pengkhianatan. Suatu ketika si lelaki besar mencari Achmad yang dianggap sebagai penghkhianat. Ketika bertemu di rumahnya yang dikepung pasukan Belanda, si lelaki berhasil menyusup ke dalam dan mencekik leher achmad, kemudian mengecap darah si Achmad sebagaimana biasa dilakukan setiap kali membunuh seseorang. Menurut lelaki yang menjadi objek lukisan, jiwa orang yang dibunuh itu akan selalu menggoda, mengganggu, mengejar dan membuat pembunuh gila. Untuk itu, darah orang yang dibunuh harus dikecap dengan tujuan untuk memiliki dan memakannya, meskipun hanya sedikit saja.
“Mudah sekali memahaminya. Apabila setelah membunuh seseorang kita merasa gugup atau berdebar-debar seolah-olah dikejar rohnya, dan karenanya kita menjadi takut atau bingung, berarti orang yang telah kita bunuh itu adalah pribadi yang besar dan berpengaruh,” kata si objek lukisan untuk meyakinkan tokoh “aku” yang sedang melukisnya. Anehnya, selama melukis si pembunuh itu, imajinasi “liar” yang berkecamuk pada tokoh “aku” adalah macan yang buas. Si lelaki besar murka, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini sebuah cerpen yang cukup menarik. RP tidak hanya berhasil bertutur tentang perjuangan dan pengkhianatan pada masa revolusi fisik, tetapi juga mampu menyuguhkan tabiat seorang pembunuh setelah memangsa korbannya dengan cara yang sangat “rasional”. Dengan gaya tutur yang bening, bernas, dan lincah, RP berhasil menyuguhkan adonan cerita yang sarat konflik, tetapi indah untuk dinikmati.
Dalam cerpen “Kepanjangannya”, RP bertutur tentang bayi tujuh bulan dalam kandungan yang tiba-tiba raib. Untuk mengenangnya, sang ayah membuat nisan dari kayu dan memahat nama bayinya. Lantas, mereka mengadakan selamatan dan membacakan doa-doa supaya arwah si bayi diterima di tempat yang layak di sisi Tuhan. Meski banyak yang menentangnya, sang ayah tetap menaburi bunga-bunga di makamnya. Suatu ketika, teman sang ayah menawari beberapa ekor anjing. Untuk mengobati kekecewaan terhadap kematian misterius anaknya yang masih dalam kandungan, sang ayah mengambil seekor anak anjing betina dan dipelihara dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, keluarga sang ayah dikaruniai beberapa anak. Mereka hidup bahagia, hingga kelak anak-anak mereka dewasa. Suatu ketika terjadi peristiwa aneh. Ketika purnama penuh di tahun kedua puluh sejak anaknya mati dalam kandungan, anjing kesayangannya berubah menjadi seorang gadis cantik. Esok harinya, kuburan anak sulungnya di halaman rumah digali. Di dalamnya terdapat sebuah peti kosong yang selanjutnya menjadi tempat peristirahatan terakhir gadis cantik jelmaan anjing kesayangan itu. Cerpen bertiti mangsa 1954 ini cukup berhasil “membombardir” benak pembaca dengan segala peristiwa yang serba mengejutkan; semacam “dongeng” modern yang dibalut dengan peristiwa-peristiwa keseharian yang sarat konflik.
Kelincahan RP dalam menuturkan kisah-kisah yang beraroma mistis tidak berhenti sampai di situ. Masih ada beberapa cerpen lain yang memiliki balutan mistis yang serba mengejutkan dan menyeramkan. Masih mengambil latar situasi pasca-revolusi fisik, RP mengajak pembaca untuk mengapresiasi cinta sejati sepasang kekasih dalam cerpen bertitel “Satu”. Si lelaki menjadi pejuang, sedangkan si perempuan menjadi relawan. Semasa hidup, mereka berikrar agar kelak makamnya disandingkan. Setelah gugur, amanat itu dilaksanakan teman-teman seperjuangannya. Tapi aneh, ketika makam tersebut digali, kerangka sang lelaki menyatu dengan kerangka si gadis. Cerpen ini ingin menyampaikan seruan moral berupa keinginan seorang rakyat yang memimpikan persatuan di negerinya yang disimbolkan dengan menyatunya kerangka sepasang kekasih di alam kubur.
Nada dan suasana yang benar-benar mencekam bisa dinikmati dalam cerpen “Si Rangka” yang bertutur tentang kegelisahan dan ketakutan seorang isteri bernama Suriah yang selalu mendengar suara biola di salah satu tembok kamarnya. Namun, suaminya tak pernah mendengarnya. Suara itu terus menggodanya, hingga suatu ketika datang seorang lelaki bernama Naryo. Kehadiran Naryo membuat Suriah selalu terusik perhatiannya. Ia melihat sepasang mata Naryo seperti lubang sumur yang sangat dalam. Suatu ketika, suara biola di balik tembok kamar berubah menjadi suara rintihan seperti orang terjepit hingga akhirnya dibongkar. Di bawah dinding tembok itu ternyata ada kerangka manusia. Pada suatu hari, Naryo mengajak Suriah untuk ikut pindah ke rumah barunya. Malam itu juga, Suriah mati. Demikian juga pada cerpen “Tanpa Judul”. Pak Prada yang mengidap penyakit jantung meninggal. Namun, pada suatu hari, tokoh aku melihat sosok Pak Prada berkelebat memasuki rumahnya. Karena penasaran, tokoh aku bergegas menuju rumah Bu Prada. Di rumah itu terdengar jerit-tangis. Ternyata, Bu Prada meninggal menyusul suaminya.
Sebuah cerpen bernapaskan “petualangan gaib” bisa dinikmati dalam cerpen bertitel “Pengejaran”. Tokoh “aku” mengejar seseorang yang telah meloncat dari kereta api karena merampas barangnya yang sangat berharga. “Aku” terus mengejarnya melintasi rerimbunan belukar dan perbukitan terjal. Ketika hendak sampai di rumah si perampas yang sangat terpencil, terjadi perkelahian seru, hingga akhirnya si perampas berhasil dirobohkan. Ketika terjadi percakapan di rumah si perampas, ia mengaku sebagai orang dari masa silam. Lalu, ia menceritakan ibunya yang buta dan ayahnya yang suka mengganggu teman-teman seperjuangan. Tokoh “aku” tertidur dan keesokan harinya, datang penduduk desa sebelah dan bercerita kalau rumah terpencil itu sudah lama kosong.
Pada cerpen “Tiga Benua”, pembaca disuguhi kisah pergulatan antara dunia manusia dan dunia jin. Beberapa tahun sebelum pecah perang, sepasang suami isteri yang baru menikah mendapat warisan yang banyak. Mereka sepakat untuk membangun sebuah rumah yang mereka inginkan. Setelah rumah yang cukup besar berhasil dibangun, mereka menjadi kaya raya dan terhormat. Si suami pedagang yang sukses. Namun, kehidupan mereka terganggu ulah pencuri. Suatu ketika seorang Arab kenalan si suami menyanggupi untuk menempatkan empat jin di setiap penjuru rumah agar aman dari pencurian. Sejak saat itu, rumah mereka aman. Jin penunggu rumah itu terdiri 3 jin laki-laki yang memperebutkan seorang jin perempuan. Suasana rumah pun sering ribut. Dari 3 jin itu, hanya tinggal 1 yang masih hidup. Dua yang lainnya mati dalam perkelahian. Jin yang menang itu pun akhirnya menikah dengan jin perempuan. Mereka memiliki beberapa anak. Ketika anak-anak mereka sudah banyak, timbul keinginan isteri jin untuk menguasai rumah itu. Jin laki-laki menyanggupinya dengan cara membuat anak pemilik rumah jatuh sakit. Akhirnya, dua di antaranya meninggal tanpa diketahui apa penyebab sakit dan kematiannya. Kini, pemilik rumah hanya memiliki dua anak. Yang satu pun akhirnya menyusul ke alam baka. Pemilik rumah mencari paranormal. Terjadilah perjuangan mengusir jin yang cukup sengit hingga berbulan-bulan. Pemilik rumah tidak lagi sanggup bertahan dan memilih pindah rumah. Namun, datanglah si Arab kenalannya yang dulu mencarikan jin penjaga rumah. Si Arab marah dan menghukum jin. Anak satu-satunya yang sakit akhirnya sembuh dari sakit. Namun, mereka tidak lagi kerasan tinggal di rumah itu karena sudah berubah menjadi rumah tua yang mulai rusak.
Sementara itu, cerpen berjudul “Setia Seekor Anjing” menuturkan kesetiaan seekor anjing terhadap “majikan”-nya. Anjing yang sangat setia terhadap majikan, tetapi galak kepada orang lain itu berbuat ulah setelah kematian sang majikan. Anjing bernama “si Boi” itu ikut makam majikannya. Keesokan harinya, ada kabar jenazah sang majikan keluar dari kuburnya, duduk di samping onggokan makam dan bersandar pada batang pohon kamboja. Akhirnya, jenazah sang majikan dikuburkan kembali dan ditunggui. Para penjaga makam terkejut ketika pada dini hari mendengar suara gonggongan anjing. Keesokan harinya ada kabar kalau sang majikan bangun kembali dari dalam kubur. Kabar ini pun tersebar luas. Akhirnya, si Boi dicari untuk ditangkap, tetapi tak seorang pun yang berhasil menemukannya. Namun, setiap malam terdengar gonggongan si Boi yang memelas, menangisi majikan yang telah meninggalkannya.
Ya, adonan kisah yang sarat dengan ketegangan, kesuraman, keharuan, kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan agaknya menjadi tema yang selalu mengusik “intuisi” RP untuk memberikan “testimoni literer” terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai genre sastra, cerpen memang tak pernah tercipta dalam situasi “kosong”. Artinya, selalu ada nilai-nilai tradisi dan budaya yang dengan amat sadar diangkat sang pengarang sebagai bagian dari pernik-pernik peradaban umat manusia.
***
Masih ada delapan cerpen lain yang tidak kalah menarik untuk dibaca dan dinikmati. “Anjing Penjaga”, “Dengan Maut”, “Jampi Cinta Seorang Nenek”, “Pasukan Terakhir”, “Rindu pada Manusia”, “Sebuah Persahabatan”, “Semalam Aku Bersama Ayahku Almarhum”, dan “Tangan Kecil” banyak membidik persoalan kemiskinan, kejahatan, cinta, perjuangan, kerinduan, persahabatan, dan kegetiran hidup. Dalam cerpen-cerpen tersebut tampak kepedulian sang pengarang (RP) terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sering terlupakan di tengah pergulatan dan dinamika hidup manusia yang demikian rumit dan kompleks.
Dalam “Anjing Penjaga” dituturkan, karena hidup miskin, seseorang tega membunuh anjing — yang selama ini setia menjaga rumahnya– di rel kereta api. Tak ampun lagi, anjing penjaga itu pun tewas mengenaskan. Menurut pemiliknya, anjing itu suka mencuri makanan, sehingga dia dan keluarganya sering menderita kelaparan. Namun, setelah kematian anjing itu, pemilik anjing justru dirundung bencana beruntun. Rumahnya sering kemasukan pencuri dan anak gadisnya dibawa lari seorang pemuda jahat. Sementara itu, dalam cerpen “Dengan Maut” dituturkan kecemasan hidup seorang pengarang menjelang eksekusi kematian. Namun, oleh komandan eksekusi yang bertubuh besar, sang pengarang diberi kesempatan untuk menulis cerita hingga akhirnya menjadi sebuah buku. Akhirnya, sang pengarang dibebaskan dari hukuman mati. Bahkan, buku yang ditulisnya selama menghadapi hukuman mati disambut gembira oleh masyarakat dan diterjemahkan ke dalam bahasa asing.
Lain lagi dengan “Jampi Cinta Seorang Nenek”. Cerpen ini bertutur tentang dendam cinta seorang nenek. Waktu muda, si nenek jatuh cinta pada seorang pemuda, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Suatu ketika terjadi “kecelakaan”. Si pemuda jagoan yang tidak dicintainya telah merenggut kegadisan si nenek hingga akhirnya menikah dan melahirkan seorang anak menjadi gadis cantik. Ia bertekad untuk mencari “ilmu” yang bisa membuat seseorang jatuh hati. Anak dan cucunya dijadikan sebagai “umpan” dan media untuk melampiaskan dendamnya.
Suasana tragis pada masa perjuangan kembali diangkat RP dalam cerpen “Pasukan Terakhir” dan “Tangan Kecil”. Cerpen “Pasukan Terakhir” bertutur tentang perjalanan jauh sejumlah lulusan SMA. Di suatu desa, mereka menginap di rumah seorang perempuan dengan disuguhi ketela pohon rebus. Tokoh “aku” tertarik pada kisah yang dituturkan nyonya rumah tentang desa yang hanya dihuni janda. Suami mereka pergi ke medan perang dan akhirnya mereka gugur sebelum bisa bertemu keluarganya. Sementara itu, “Tangan Kecil” mendedahkan cerita tentang sisa pasukan yang sampai di tepi batas sebuah desa. Dalam keadaan lapar, sisa pasukan berteduh di rumah seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Di bawah ancaman ujung bayonet, kepala pasukan memaksa si ibu untuk membuatkan bubur. Karena terpaksa, si ibu keluar rumah sambil menggendong bayinya. Ada prasangka buruk bahwa perempuan itu akan menyembelih anaknya dan dagingnya disuguhkan kepada pasukan. Si perempuan terus sibuk di dapur. Setelah matang, sambil menunduk dan menangis, si ibu menyiapkan hidangan. Karena sudah tak sabar, pasukan menyerbu hidangan daging. Terjadilah kehebohan. Salah satu pasukan melihat ada tangan kecil di balik daging yang dimasak. Mereka muntah-muntah. Pasukan memaki-maki. Si ibu menangis. Perempuan itu dianggap telah menghidangkan daging bayinya untuk mereka. Lantai rumah jadi berantakan. Penuh kotoran. Namun, ternyata bayinya tertidur lelap beralas amben kecil dekat tumpukan kayu.
Cerpen dramatis yang mengangkat sisi-sisi kemanusiaan dapat dinikmati pada cerpen “Rindu pada Manusia”, “Sebuah Persahabatan”, dan “Semalam Aku Bersama Ayahku Almarhum”. Dalam cerpen “Rindu pada Manusia” dituturkan kisah seorang gadis kecil anak nelayan yang berusaha mencari bapaknya. Si gadis melarikan diri dari kampung. Penduduk kampung mencarinya. Namun, mereka tidak tahu di mana si gadis berada. Orang-orang mengira jika ia tenggelam dan terseret gelombang laut. Ternyata, ia naik pohon kelapa di tepi pantai dan bersembunyi si sana, lari dari dunia, lari dari manusia yang tak pernah bisa memahaminya. Di atas sana, ia merasakan kebahagiaan meski sesaat; ia merasa jauh dari kebencian. Empat hari, lima hari, enam hari, ia tak juga merasa lapar. Badannya juga tak bergerak, hanya sebentar ia menggantungkan kaki dan merentangkan tangan. Dari atas, ia melihat kelakuan orang-orang yang mencarinya. Ia merasa betapa bodohnya manusia. Pada hari keenam, ia merasa aneh pada dirinya. Badannya lemas seolah-olah tak bertenaga dan kepalanya pusing. Ia tiba-tiba merasa diserang kerinduan: rindu kepada manusia. Ia rasanya ingin berteriak memanggil manusia, memanggil siapa saja. Tapi badannya sudah tak bertenaga lagi. Gadis itu akhirnya jatuh ke bumi, ke pangkuannya. Keinginannya agar lekas sampai di dunia tercapai, tapi bagaimana dengan kerinduannya pada manusia?
“Sebuah Persahabatan” misterius masih tersisa dalam cerpen yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Ketika sepasang suami-istri membuka album foto, si suami kaget atas pertanyaan yang diajukan isterinya. Si Darma yang telah meninggal ditembak Belanda ternyata muncul di sebuah foto. Bahkan, menurut pengakuan si isteri, Darma datang dan ikut makan pada saat pesta tahun baru sebelum mereka resmi menikah. Ternyata, Darma menepati janjinya, datang di hari yang penting bagi sepasang suami-isteri itu. Sang suami terharu dan menitikkan air mata ketika mengenang kembali masa persahabatan yang kekal.
Kesetiaan terhadap tugas dan keluarga tercermin dalam cerpen “Semalam Aku Bersama Ayahku Almarhum”. Tokoh “aku” yang dituntut harus segera menyelesaikan pekerjaan tak bisa pulang mudik lebaran ke Jakarta. Ia tinggal sendirian di sebuah pondokan. Pada malam menjelang lebaran esok hari, si “aku” tidak bisa tidur. Tiba-tiba saja, “aku” merasakan seseorang yang datang ke kamar tidurnya. Ya, almarhum ayahnya yang seorang pejuang menemuinya menjelang lebaran dan terjadilah percakapan. Banyak hal yang diperbincangkan. Tokoh aku merasa bangga dengan ayahnya yang gugur di medan perang.
***
20 cerpen yang terkumpul dalam antologi ini memang terasa belum cukup untuk menakar eksistensi RP dalam menggeluti dunia penciptaan cerpen. Namun, setidaknya bisa menjadi bukti otentik tentang keberpihakan RP terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sering terabaikan. Kisah-kisah kemanusiaan yang dituturkan dengan gaya tutur yang bening, bernas, dan lincah bisa dibilang sebagai sebuah “kesaksian literer” terhadap pernik-pernik peradaban yang kerap terabaikan banyak orang akibat dinamika hidup yang makin rumit dan kompleks.
Yang menonjol dalam cerpen-cerpen RP sejatinya bukan persoalan mistik, klenik, atau hal-hal yang menyeramkan lainnya semata, melainkan upaya sang pengarang untuk mengingatkan entitas kemanusiaan yang sering terenggut oleh otoritas kekuasaan. Ada pesan-pesan moral yang cukup kuat yang selalu tersirat dalam setiap cerpennya. Seandainya muncul balutan suasana menakutkan, menyeramkan, “sonyaruri”, atau “dunia lain” muncul dalam cerpen-cerpennya, hal ini tak lepas dari gaya bertutur RP yang memang telah menjadi semacam “branding” kreativitasnya dalam berkarya.
Manifestasi gaya bertutur yang serba “seram” dalam mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dalam cerpen adalah hadirnya sebuah teks yang selalu mengundang banyak tafsir terhadap jalinan peristiwa yang dituturkan. Tak berlebihan kalau setiap membaca cerpen RP selalu muncul tafsir baru dalam memaknai peristiwa yang dialami tokoh dalam setiap cerpennya. Meski dihasilkan pada kisaran tahun 1950-an, cerpen-cerpen dalam antologi ini tetap menghadirkan tafsir baru yang bisa jadi masih amat relevan dalam konteks kekinian.
Kehadiran antologi ini tentu diharapkan makin memperkaya khasanah Sastra Indonesia mutakhir di tengah arus kehadiran cerpen yang terus membanjir dari tangan sastrawan kita. Selain itu, juga mampu mengundang “animo” para pemerhati, pengamat, dan ahli sastra untuk menelisik dan membedah lebih tajam cerpen-cerpen karya almarhum Riyono Pratikto. Semoga Almarhum menemukan kedamaian dan kebahagiaan abadi di alamnya yang baru. ***
Kendal, 18 Februari 2016
Sawali Tuhusetya (guru dan blogger, tinggal di Kendal-Jawa Tengah)
——————————
Yang ingin memiliki kumpulan cerpen ini, silakan kontak ke putra Almarhum Riyono Pratikto, Mas Riyogarta yang telah memprakarsai terbitnya buku ini.
 Ditulis dalam gaya yang unik dengan judul yang menyatu dalam tubuh puisi, membuat buku ini lain daripada yang lain. Ada puisi yang demikian pendek bahkan lebih pendek dari judulnya, ada puisi yang begitu panjang, yang jika pembaca tak bisa menyiasatinya niscaya akan kehabisan oksigen tatkala membacanya. Puisi yang sangat pendek seperti puisi yang berjudul ‘BICARA DARI BATU KE BATU’, isinya hanya tiga kata : sudahkah wahai luka (halaman 9). Dan puisi yang panjang bahkan sampai tiga halaman penuh, seperti pada puisi yang berjudul ‘POLITIK-HUKUM-PUISI DALAM GUMAMKU’ di halaman 4 sampai dengan 6, puisi berjudul HALAMAN DARAH, yang panjangnya sampai empat lembar full di halaman 32 sampai dengan halaman 35.
Ditulis dalam gaya yang unik dengan judul yang menyatu dalam tubuh puisi, membuat buku ini lain daripada yang lain. Ada puisi yang demikian pendek bahkan lebih pendek dari judulnya, ada puisi yang begitu panjang, yang jika pembaca tak bisa menyiasatinya niscaya akan kehabisan oksigen tatkala membacanya. Puisi yang sangat pendek seperti puisi yang berjudul ‘BICARA DARI BATU KE BATU’, isinya hanya tiga kata : sudahkah wahai luka (halaman 9). Dan puisi yang panjang bahkan sampai tiga halaman penuh, seperti pada puisi yang berjudul ‘POLITIK-HUKUM-PUISI DALAM GUMAMKU’ di halaman 4 sampai dengan 6, puisi berjudul HALAMAN DARAH, yang panjangnya sampai empat lembar full di halaman 32 sampai dengan halaman 35.
 Pada sebuah ruang perjumpaan, di saat yang memang telah menjadi takdirnya maka ada satu nama sebagai fokus pembicaraan, ia adalah sosok manusia yang tak pernah berhenti bergerak dalam satu pusat edar – yang diyakini olehnya sebagai daya hidup tak berkesudahan : pusat edar sastra – hal lain boleh saja runtuh boleh saja ditinggalkan boleh saja dilepaskan, tetapi dalam daya hidup yang ada di pusat edar bernama sastra ternyata banyak yang teramat manis untuk selalu dilekatkan untuk selalu direkatkan, bahkan antara jejak dan gurat-gurat garis di telapak kaki sulit dipisahkan.
Pada sebuah ruang perjumpaan, di saat yang memang telah menjadi takdirnya maka ada satu nama sebagai fokus pembicaraan, ia adalah sosok manusia yang tak pernah berhenti bergerak dalam satu pusat edar – yang diyakini olehnya sebagai daya hidup tak berkesudahan : pusat edar sastra – hal lain boleh saja runtuh boleh saja ditinggalkan boleh saja dilepaskan, tetapi dalam daya hidup yang ada di pusat edar bernama sastra ternyata banyak yang teramat manis untuk selalu dilekatkan untuk selalu direkatkan, bahkan antara jejak dan gurat-gurat garis di telapak kaki sulit dipisahkan. Saya publikasikan kembali sebuah esai menarik karya Bang Asa (Ali Syamsudin Arsi); salah satu penyair Indonesia asal Kalimantan Selatan yang cukup kreatif dan produktif. Tulisan ini cukup panjang karena disertakan juga beberapa puisi karya penyair asal Kalimantan Selatan yang terkumpul dalam buku kumpulan puisi Memo untuk Presiden. Namun, karena terbatasnya ruang, karya-karya puisi tersebut tidak saya publikasikan dalam postingan ini. Yang ingin membaca dan mengapresiasinya, silakan unduh
Saya publikasikan kembali sebuah esai menarik karya Bang Asa (Ali Syamsudin Arsi); salah satu penyair Indonesia asal Kalimantan Selatan yang cukup kreatif dan produktif. Tulisan ini cukup panjang karena disertakan juga beberapa puisi karya penyair asal Kalimantan Selatan yang terkumpul dalam buku kumpulan puisi Memo untuk Presiden. Namun, karena terbatasnya ruang, karya-karya puisi tersebut tidak saya publikasikan dalam postingan ini. Yang ingin membaca dan mengapresiasinya, silakan unduh  “Biarkan pendengar yang menyimpulkan sendiri! Tugas Sampeyan hanyalah membaca, membaca, dan membaca. Titik! Tidak perlu pakai ekspresi! Sampeyan digaji bukan untuk bermain drama di ruang berita!” begitu konon kata sang majikan yang pernah disampaikan teman Kang Badrun saat masih mengadu nasib di kota megapolitan.
“Biarkan pendengar yang menyimpulkan sendiri! Tugas Sampeyan hanyalah membaca, membaca, dan membaca. Titik! Tidak perlu pakai ekspresi! Sampeyan digaji bukan untuk bermain drama di ruang berita!” begitu konon kata sang majikan yang pernah disampaikan teman Kang Badrun saat masih mengadu nasib di kota megapolitan. Dari kacamata politik, bisa jadi perilaku yang penuh improvisasi dengan menghalalkan segala cara untuk memikat perhatian rakyat menjadi “pakem” wajib yang mesti diikuti para politisi untuk mendapatkan kemenangan. Namun, dari sudut pendidikan politik, perilaku ala Machiavelli semacam itu tidak saja melukai nurani rakyat yang sangat mendambakan munculnya politisi elegan dan kesatria, tetapi juga menanamkan perilaku dan karakter anomali kepada generasi muda. Setidaknya, perilaku “jahat” yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan akan tertanam kuat dalam memori anak-anak bangsa hingga kelak mereka dewasa. Implikasinya, mereka akan meneladani perilaku jahat yang sarat anomali itu dalam kehidupan mereka kelak.
Dari kacamata politik, bisa jadi perilaku yang penuh improvisasi dengan menghalalkan segala cara untuk memikat perhatian rakyat menjadi “pakem” wajib yang mesti diikuti para politisi untuk mendapatkan kemenangan. Namun, dari sudut pendidikan politik, perilaku ala Machiavelli semacam itu tidak saja melukai nurani rakyat yang sangat mendambakan munculnya politisi elegan dan kesatria, tetapi juga menanamkan perilaku dan karakter anomali kepada generasi muda. Setidaknya, perilaku “jahat” yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan akan tertanam kuat dalam memori anak-anak bangsa hingga kelak mereka dewasa. Implikasinya, mereka akan meneladani perilaku jahat yang sarat anomali itu dalam kehidupan mereka kelak.  Meskipun demikian, setahun yang lewat juga sudah banyak memberikan pelajaran berharga buat hidup dan kehidupan. Tidak ada salahnya perjalanan hidup yang setahun lamanya melintasi usia kita dijadikan sebagai momen berharga untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan itulah yang sesungguhnya merupakan resolusi hakiki, tanpa harus ditulis dan digembar-gemborkan. Apa yang akan terjadi setahun mendatang juga seringkali merupakan sebuah misteri. Kata hati, perilaku, sikap, tindakan, dan perbuatan yang menyertai hidup kita dalam memasuki sebuah lorong misteri itu sejatinya juga merupakan sebuah resolusi itu sendiri.
Meskipun demikian, setahun yang lewat juga sudah banyak memberikan pelajaran berharga buat hidup dan kehidupan. Tidak ada salahnya perjalanan hidup yang setahun lamanya melintasi usia kita dijadikan sebagai momen berharga untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan itulah yang sesungguhnya merupakan resolusi hakiki, tanpa harus ditulis dan digembar-gemborkan. Apa yang akan terjadi setahun mendatang juga seringkali merupakan sebuah misteri. Kata hati, perilaku, sikap, tindakan, dan perbuatan yang menyertai hidup kita dalam memasuki sebuah lorong misteri itu sejatinya juga merupakan sebuah resolusi itu sendiri.  Ketika memasuki Ramadhan 1436 H ini, saya tiba-tiba kembali terusik untuk “menghidupkan” kembali spirit dan semangat ngeblog. “Sejauh-jauh burung terbang, akhirnya kembali juga ke sarangnya”, begitulah kata orang tua kita. Sejauh apa pun saya melangkah dan berlari, toh pada akhirnya saya harus kembali ke “habitat” saya di kompleks blogsphere. Apa pun yang terjadi, ngeblog sudah menjadi bagian dari “kebutuhan” untuk bereksistensi diri. Sungguh akan semakin naif apabila spirit ngeblog yang sudah terbangun sejak 2007 itu terus-terusan terjun bebas dan tiarap, hingga akhirnya terkubur dalam deraan sang waktu.
Ketika memasuki Ramadhan 1436 H ini, saya tiba-tiba kembali terusik untuk “menghidupkan” kembali spirit dan semangat ngeblog. “Sejauh-jauh burung terbang, akhirnya kembali juga ke sarangnya”, begitulah kata orang tua kita. Sejauh apa pun saya melangkah dan berlari, toh pada akhirnya saya harus kembali ke “habitat” saya di kompleks blogsphere. Apa pun yang terjadi, ngeblog sudah menjadi bagian dari “kebutuhan” untuk bereksistensi diri. Sungguh akan semakin naif apabila spirit ngeblog yang sudah terbangun sejak 2007 itu terus-terusan terjun bebas dan tiarap, hingga akhirnya terkubur dalam deraan sang waktu. Maka, ketika media sosial “menghebohkan” kepindahan agama Lukman Sardi, aktor yang pernah membintangi K.H. Akhmad Dahlan dalam “Sang Pencerah” itu, bagi saya, merupakan soal klasik. Toh, hanya lantaran faktor popularitas si Lukman Sardi yang membuat persoalan ini mencuat ke permukaan. Toh, sesungguhnya bukan hanya putra Idris Sardi itu saja yang menunjukkan spirit religiusitas “mulur-mungkret” hingga meyakinkannya untuk “bermigrasi” ke agama tertentu. Di sekeliling kita, tidak sedikit orang yang menunjukkan fenomena serupa. Toh, juga tak ada seorang pun yang mempersoalkan. Tuhan pun memberikan pilihan “jalan hidup”, termasuk agama, kepada hamba-Nya. Seandainya separuh penduduk di muka bumi ini ramai-ramai pindah agama; dari Islam ke non-Islam, misalnya, tak sedikit pun mengurangi kebesaran Tuhan.
Maka, ketika media sosial “menghebohkan” kepindahan agama Lukman Sardi, aktor yang pernah membintangi K.H. Akhmad Dahlan dalam “Sang Pencerah” itu, bagi saya, merupakan soal klasik. Toh, hanya lantaran faktor popularitas si Lukman Sardi yang membuat persoalan ini mencuat ke permukaan. Toh, sesungguhnya bukan hanya putra Idris Sardi itu saja yang menunjukkan spirit religiusitas “mulur-mungkret” hingga meyakinkannya untuk “bermigrasi” ke agama tertentu. Di sekeliling kita, tidak sedikit orang yang menunjukkan fenomena serupa. Toh, juga tak ada seorang pun yang mempersoalkan. Tuhan pun memberikan pilihan “jalan hidup”, termasuk agama, kepada hamba-Nya. Seandainya separuh penduduk di muka bumi ini ramai-ramai pindah agama; dari Islam ke non-Islam, misalnya, tak sedikit pun mengurangi kebesaran Tuhan. Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia mengundang Presiden AS dan Prancis terbang bersama buat keliling dunia. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya.
Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia mengundang Presiden AS dan Prancis terbang bersama buat keliling dunia. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya. Jika guru diwajibkan melakukan penelitian, maka bisa berdampak pada gagalnya pelaksanaan tugas utama guru. Guru dan dosen memang pendidik, tetapi tugas utama guru itu berbeda dengan dosen. Guru, terang Sulistiyo, adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini terdapat dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1). Sedangkan, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini berdasarkan Undang-undang tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 2.
Jika guru diwajibkan melakukan penelitian, maka bisa berdampak pada gagalnya pelaksanaan tugas utama guru. Guru dan dosen memang pendidik, tetapi tugas utama guru itu berbeda dengan dosen. Guru, terang Sulistiyo, adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini terdapat dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1). Sedangkan, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini berdasarkan Undang-undang tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 2. Ada apa? Tanpa bermaksud berapologi, ngeblog memang memiliki dinamika tersendiri. “Mulur-mungkret”, begitulah kata orang tua kita. Sebagai aktivitas kedua, ngeblog memang tidak selalu bisa berada di depan secara konsisten. Dulu, ketika aktivitas menulis masih mengandalkan media cetak sebagai media mainstream untuk berekspresi, kreativitas menulis, mesti diakui, justru makin menemukan bentuknya dalam bereksistensi diri. Namun, ketika kejayaan media cetak memasuki situasi senjakala, jejak kepenulisan saya ikut menyurut. Kalau toh ada, tulisan yang tersaji, baik melalui blog maupun sekadar tumpahan unek-unek di jejaring sosial, kualitasnya tak bisa dibandingkan dengan tulisan yang berhasil menembus ketatnya barikade redaksi media cetak.
Ada apa? Tanpa bermaksud berapologi, ngeblog memang memiliki dinamika tersendiri. “Mulur-mungkret”, begitulah kata orang tua kita. Sebagai aktivitas kedua, ngeblog memang tidak selalu bisa berada di depan secara konsisten. Dulu, ketika aktivitas menulis masih mengandalkan media cetak sebagai media mainstream untuk berekspresi, kreativitas menulis, mesti diakui, justru makin menemukan bentuknya dalam bereksistensi diri. Namun, ketika kejayaan media cetak memasuki situasi senjakala, jejak kepenulisan saya ikut menyurut. Kalau toh ada, tulisan yang tersaji, baik melalui blog maupun sekadar tumpahan unek-unek di jejaring sosial, kualitasnya tak bisa dibandingkan dengan tulisan yang berhasil menembus ketatnya barikade redaksi media cetak. “Karena kita masih dalam tahap berkembang,” jawab Putri, “Kita perlu belajar dari orang lain dengan cara membaca karya-karya mereka. Karya-karya sastra dari orang-orang yang sudah berpengalaman bisa jadi sumber inspirasi kita, lho. Jadi menurutku, kalau cuma belajar sendiri belum tentu cukup.”
“Karena kita masih dalam tahap berkembang,” jawab Putri, “Kita perlu belajar dari orang lain dengan cara membaca karya-karya mereka. Karya-karya sastra dari orang-orang yang sudah berpengalaman bisa jadi sumber inspirasi kita, lho. Jadi menurutku, kalau cuma belajar sendiri belum tentu cukup.” Meski masih terus mengalami perkembangan serta belum ada definisi baku namun jika dirunut secara kebahasaan kata “terorisme” di antaranya merujuk pada terrere (bahasa latin) yang berarti menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Dalam khasanah bahasa Inggris dikenal pula istilah to terrorize (menakuti-nakuti) yang diturunkan menjadi kata terrorist (pelaku teror), terrorism (membuat ketakutan atau membuat gentar), serta terror (ketakutan atau kecemasan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara singkat terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Dari pengertian sederhana tersebut tampak bahwa pada dasarnya aktivitas terorisme selalu terkait dengan unsur-unsur kekerasan (oleh pelaku) hingga menyebabkan ketakutan (bagi korban) dalam rangka mencapai tujuan (tertentu).
Meski masih terus mengalami perkembangan serta belum ada definisi baku namun jika dirunut secara kebahasaan kata “terorisme” di antaranya merujuk pada terrere (bahasa latin) yang berarti menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Dalam khasanah bahasa Inggris dikenal pula istilah to terrorize (menakuti-nakuti) yang diturunkan menjadi kata terrorist (pelaku teror), terrorism (membuat ketakutan atau membuat gentar), serta terror (ketakutan atau kecemasan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara singkat terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Dari pengertian sederhana tersebut tampak bahwa pada dasarnya aktivitas terorisme selalu terkait dengan unsur-unsur kekerasan (oleh pelaku) hingga menyebabkan ketakutan (bagi korban) dalam rangka mencapai tujuan (tertentu). Demikian juga halnya dengan teks puisi. Sebagai genre sastra, teks puisi juga tak pernah hadir dalam situasi kosong. Ia senantiasa mengusung berbagai persoalan yang berkelindan dalam diri personal sang penyair (jagat cilik) dan berbagai dinamika sosial yang terjadi di seputar kehidupan sang penyair (jagat gedhe). Melalui kepekaan intuitifnya, sang penyair senantiasa terlibat dalam pergulatan kreatif untuk menyuarakan kegelisahan yang mengerak dalam gendang nuraninya. Melalui bahasa sebagai medium utama dalam berekspresi, sang penyair melakukan transpirasi total kepenyairan sesuai dengan gaya tutur dan licentia poetica yang dimilikinya. Dalam proses pergulatan kreatif yang semacam itu lahirlah berbagai genre puisi dengan corak khasnya masing-masing.
Demikian juga halnya dengan teks puisi. Sebagai genre sastra, teks puisi juga tak pernah hadir dalam situasi kosong. Ia senantiasa mengusung berbagai persoalan yang berkelindan dalam diri personal sang penyair (jagat cilik) dan berbagai dinamika sosial yang terjadi di seputar kehidupan sang penyair (jagat gedhe). Melalui kepekaan intuitifnya, sang penyair senantiasa terlibat dalam pergulatan kreatif untuk menyuarakan kegelisahan yang mengerak dalam gendang nuraninya. Melalui bahasa sebagai medium utama dalam berekspresi, sang penyair melakukan transpirasi total kepenyairan sesuai dengan gaya tutur dan licentia poetica yang dimilikinya. Dalam proses pergulatan kreatif yang semacam itu lahirlah berbagai genre puisi dengan corak khasnya masing-masing. Puisi-puisi karya Setia Naka Andrian (SNA) yang terkumpul dalam Perayaan Laut (PL) pun –dalam penafsiran awam saya– tak luput dari pergulatan yang semacam itu. SNA dengan amat sadar memilih puisi sebagai teks yang dianggap tepat untuk memberikan “kesaksian” dan menyuarakan kegelisahan yang mengendap dalam ruang batinnya. Kepiawaian dalam merawi kosakata, idiom, atau langgam bahasa agaknya dimanfaatkan benar untuk mengekspresikan berbagai persoalan yang bernaung di bawah jagat cilik dan jagat gedhe yang membayang dalam gendang nuraninya. Tak berlebihan kalau sejumlah puisi yang terantologikan dalam PL menyiratkan berbagai persoalan personal dan sosial yang menggelisahkan nuraninya; semacam cinta, idealisme, religi, atau hajat kehidupan yang yang lain.
Puisi-puisi karya Setia Naka Andrian (SNA) yang terkumpul dalam Perayaan Laut (PL) pun –dalam penafsiran awam saya– tak luput dari pergulatan yang semacam itu. SNA dengan amat sadar memilih puisi sebagai teks yang dianggap tepat untuk memberikan “kesaksian” dan menyuarakan kegelisahan yang mengendap dalam ruang batinnya. Kepiawaian dalam merawi kosakata, idiom, atau langgam bahasa agaknya dimanfaatkan benar untuk mengekspresikan berbagai persoalan yang bernaung di bawah jagat cilik dan jagat gedhe yang membayang dalam gendang nuraninya. Tak berlebihan kalau sejumlah puisi yang terantologikan dalam PL menyiratkan berbagai persoalan personal dan sosial yang menggelisahkan nuraninya; semacam cinta, idealisme, religi, atau hajat kehidupan yang yang lain. Dalam situasi semacam itu, upaya untuk mendokumentasikan dan memublikasikan karya-karya sastrawan yang meninggal 30 Oktober 2005 ini menjadi penting dan relevan untuk memperkaya khazanah sastra Indonesia mutakhir. Penting dan relevan bukan sekadar untuk menunjukkan bukti bahwa negeri ini memiliki sosok sastrawan yang rendah hati dan konsisten, meskipun tekanan politik rezim Orde Baru nyata-nyata telah menyingkirkannya dari panggung kesusastraan Indonesia mutakhir. Juga bukan sekadar latah untuk mengenang romantika kreativitas seorang RP pada masa suburnya dalam berkarya, melainkan lantaran dari sisi literer karya-karyanya memang sangat layak untuk diapresiasi para pencinta, pemerhati, dan pengamat sastra.
Dalam situasi semacam itu, upaya untuk mendokumentasikan dan memublikasikan karya-karya sastrawan yang meninggal 30 Oktober 2005 ini menjadi penting dan relevan untuk memperkaya khazanah sastra Indonesia mutakhir. Penting dan relevan bukan sekadar untuk menunjukkan bukti bahwa negeri ini memiliki sosok sastrawan yang rendah hati dan konsisten, meskipun tekanan politik rezim Orde Baru nyata-nyata telah menyingkirkannya dari panggung kesusastraan Indonesia mutakhir. Juga bukan sekadar latah untuk mengenang romantika kreativitas seorang RP pada masa suburnya dalam berkarya, melainkan lantaran dari sisi literer karya-karyanya memang sangat layak untuk diapresiasi para pencinta, pemerhati, dan pengamat sastra. Selain memilih Ketua Umum Agupena Pusat yang baru, menetapkan/mengubah AD/ART Agupena, memusyawarahkan berbagai permasalahan internal Agupena, dan merumuskan berbagai rekomendasi demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, baik untuk dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Agupena maupun diusulkan kepada berbagai pihak terkait, Munas yang akan dihadiri Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. H. Fasli Djalal dan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banten, Drs. H. Hudaya Latuconsina itu, juga meluncurkan buku Bunga Rampai Pendidikan bertajuk Membangun Kapasitas Guru Penulis yang merupakan kumpulan esai pendidikan karya para penggiat Agupena di seluruh tanah air. Selain itu, juga pemberian anugerah Agupena Award kepada para tokoh yang dinilai memiliki jasa besar terhadap kelahiran Agupena.
Selain memilih Ketua Umum Agupena Pusat yang baru, menetapkan/mengubah AD/ART Agupena, memusyawarahkan berbagai permasalahan internal Agupena, dan merumuskan berbagai rekomendasi demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, baik untuk dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Agupena maupun diusulkan kepada berbagai pihak terkait, Munas yang akan dihadiri Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. H. Fasli Djalal dan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banten, Drs. H. Hudaya Latuconsina itu, juga meluncurkan buku Bunga Rampai Pendidikan bertajuk Membangun Kapasitas Guru Penulis yang merupakan kumpulan esai pendidikan karya para penggiat Agupena di seluruh tanah air. Selain itu, juga pemberian anugerah Agupena Award kepada para tokoh yang dinilai memiliki jasa besar terhadap kelahiran Agupena. Sejatinya, guru merupakan pencerah peradaban. Dari tangannya telah lahir banyak tokoh bersejarah –dengan semangat zamannya– yang telah berhasil menorehkan tinta emas dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Dinamika hidup dan kehidupan negeri ini, dengan segenap keriuhan kemajuan, modernitas, dan globalitasnya, tak luput dari sentuhan seorang guru. Beragam profesi –dengan berbagai disiplin ilmunya masing-masing– yang tersebar di seantero negeri, diakui atau tidak, pernah mendapatkan sentuhan “tangan dingin” seorang guru. Meski jasa mereka tak jarang terabaikan, kehadiran sosok guru tak pernah tergantikan. Mereka tetap berada di garda terdepan dalam memberikan pencerahan di tengah dinamika dan silang-sengkarutnya peradaban.
Sejatinya, guru merupakan pencerah peradaban. Dari tangannya telah lahir banyak tokoh bersejarah –dengan semangat zamannya– yang telah berhasil menorehkan tinta emas dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Dinamika hidup dan kehidupan negeri ini, dengan segenap keriuhan kemajuan, modernitas, dan globalitasnya, tak luput dari sentuhan seorang guru. Beragam profesi –dengan berbagai disiplin ilmunya masing-masing– yang tersebar di seantero negeri, diakui atau tidak, pernah mendapatkan sentuhan “tangan dingin” seorang guru. Meski jasa mereka tak jarang terabaikan, kehadiran sosok guru tak pernah tergantikan. Mereka tetap berada di garda terdepan dalam memberikan pencerahan di tengah dinamika dan silang-sengkarutnya peradaban.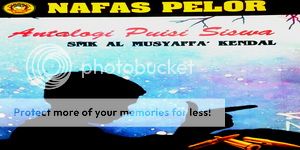 Namun, saya juga gembira, kalau pada akhirnya puisi menjadi bahasa universal yang bisa diakrabi oleh siapa pun, tanpa membedakan dari mana mereka berasal dan dari latar belakang kehidupan macam apa mereka berada. Ini artinya, puisi telah menjadi “bahasa kehidupan” yang mampu menembus batas-batas primordial, pendidikan, dan status sosial. Siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, sah-sah saja seseorang menjadikan puisi sebagai bagian dari ekspresi kehidupan. Demikian juga halnya dengan anak-anak SMK Al Musyaffa’ Kendal. Mereka telah menjadi bagian dari dunia sastra, khususnya puisi, dan akan tercatat dalam “sejarah” kehidupan bahwa mereka pernah merasakan dinamika dunia penciptaan puisi yang bersentuhan langsung dengan domain imajinasi yang sesekali “liar” dan mengejutkan.
Namun, saya juga gembira, kalau pada akhirnya puisi menjadi bahasa universal yang bisa diakrabi oleh siapa pun, tanpa membedakan dari mana mereka berasal dan dari latar belakang kehidupan macam apa mereka berada. Ini artinya, puisi telah menjadi “bahasa kehidupan” yang mampu menembus batas-batas primordial, pendidikan, dan status sosial. Siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, sah-sah saja seseorang menjadikan puisi sebagai bagian dari ekspresi kehidupan. Demikian juga halnya dengan anak-anak SMK Al Musyaffa’ Kendal. Mereka telah menjadi bagian dari dunia sastra, khususnya puisi, dan akan tercatat dalam “sejarah” kehidupan bahwa mereka pernah merasakan dinamika dunia penciptaan puisi yang bersentuhan langsung dengan domain imajinasi yang sesekali “liar” dan mengejutkan.